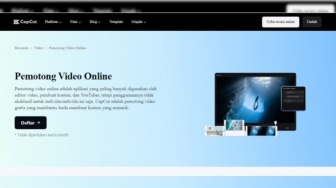SuaraJawaTengah.id - Tragedi 1965 menjadi tsunami politik yang merenggut kemanusiaan. Merampas anak-anak dari buaian para ibu.
Mia Bustam salah seorang korbannya. Aktif sebagai anggota Lekra, menyebabkan Mia 13 tahun berpindah-pindah tempat penahanan tanpa pernah diadili.
Istri pertama bapak seni rupa modern, Sudjojono ini kenyang merasakan dinginnya lantai penjara Wirogunan, Benteng Vredeburg, penjara Plantungan, Wleri, dan Kendal, hingga akhirnya dibebaskan dari penjara perempuan Bulu, 27 Juli 1978.
Pada Oktober 2009, kami menemui Mia Bustam di rumahnya yang asri di Kampung Kandang, Cinere, Jakarta Selatan. Berjarik jawa, Mia Bustam hangat menyambut kami di ruang tamu.
Baca Juga:AHY Ceritakan Kesaksian Kakeknya yang Dikenal Sebagai Penumpas PKI
Namaku Mia Bustam. Resiko sebagai anggota Lembaga Kesenian Rakyat, mendamparkanku ke lantai penjara dingin sisa kolonial ini. Aku bersama ribuan kawan lainnya, dicampakkan, dibuang, dan dihilangkan oleh kuasa rezim kesewenangan.
Apa salahnya, meyakini seni yang bukan hanya untuk seni. Apa salahnya menjadi anggota PKI.
“Berdiri kau. Sana bersandar pada dinding.”
Seorang pemuda yang ditugasi menginterogasi para tahanan PKI di Benteng Vredeburg membantakku.
“Kenapa kau jadi anggota Lekra! Tak tahu kau, Lekra itu mantel PKI!,” Matanya yang merah darah loncat menikamku.
Baca Juga:Survei SMRC: 37 Juta Warga Indonesia Percaya PKI Akan Bangkit Lagi
Kembali dia menghardik. “Bawa perintah apa dari Jakarta?”
Belakangan aku tahu pemuda itu bukan serdadu RPKAD, pimpinan Letkol Sarwo Edhi Wibowo yang ditugaskan memburu orang-orang yang dituduh anggota PKI di sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Dia mahasiswa Universitas Indonesia. Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang direkrut tentara karena piawai mengamuk dan memaki.
Aku diam. Tak ada alasan menjawab pertanyaan pria kesurupan ini. Mendadak dia mencabut pisau dan melemparkannya ke arahku.Crok! Pisau itu menancap di dinding beberapa senti di atas kepalaku.
Aku terkesiap. Jantungku berhenti. Hatiku berdesir, nafas tercekat berhenti di kerongkongan. “Tiba sudah ajalku,” dalam hati.
Dia melangkah perlahan ke arahku. Matanya nyalang haus darah. Dicabutnya pisau tadi dan kembali dilempar ke arahku berkali-kali. Menancap di kanan, kiri leherku. Nyaris merobek urat nadi di batang tenggorokan. Mulutnya terus mendesiskan cacian. Mengalirkan bisa kata-kata dari lidahnya yang bercabang.